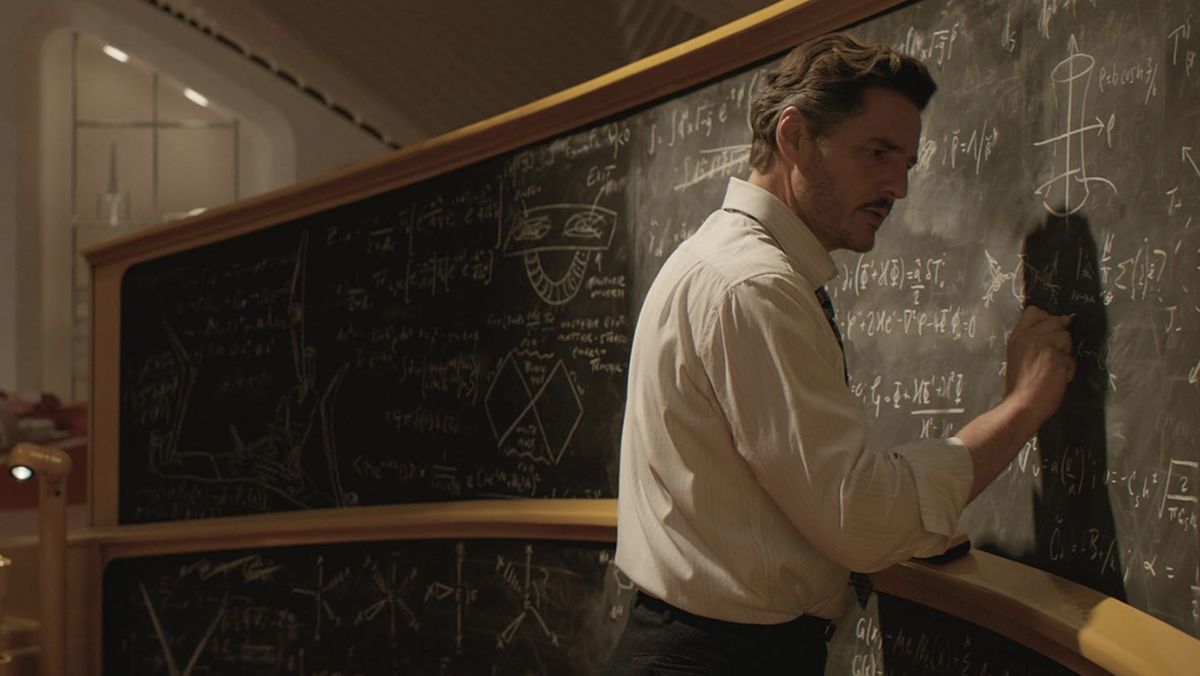Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Padel. Inilah olahraga baru yang sedang jadi tren. Saking ngetrennya, sampai-sampai tak boleh ada sedikit tanah kosong. Lengah sedikit, tiba-tiba tanah kosong jadi lapangan padel. Tanah yang Juni lalu penuh dengan kotoran kambing dan sapi, kini berubah jadi lapangan padel mewah. Begitulah tren yang sedang mewabah di kota besar, terutama Jakarta Selatan.
Padel jadi tak sekadar olahraga. Tapi bisa juga dimaknai sebagai simbol sosial kalangan kelas atas. Bagaimana tidak? Harga sewa lapangan untuk bermain padel berkisar Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu per jam.
Saya mencoba observasi kecil-kecilan di satu spot bermain padel di Jalarta Selatan. Tampak parkirannya penuh dengan mobil-mobil level atas. Jangan harap liat ada mobil low cost green car (LCGC) parkir di sana.
Ada hal yang semacam jadi ritual para padel mania. Selesai bermain, biasanya padel mania mengunggah berfoto bersama. Foto kemudian diunggah ke media sosial masing-masing pemain. Foto dengan pose di tengah lapangan atau depan net. Tanpa disadari, ritual inilah yang menyebabkan padel mewabah.
Mengutip hasil riset yang dimuat di laman Forbes, 80 persen konsumen Amerika Serikat terpengaruh unggahan teman mereka di media sosial (Kowalewicz, 2022). Tren padel mencerminkan konsep corong pemasaran (marketing funnel).
Konsep klasik yang pertama kali diperkenalkan St Elmo Lewis pada 1898. Marketing funnel secara sederhana adalah proses konsumen dari hingga memutuskan membeli produk atau jasa. Lewis membagi proses tersebut pada empat tahap, yaitu awareness (menyadari), interest (tertarik), desire (keinginan), hingga action (tindakan).
Jika dijelaskan secara sederhana adalah bagaimana membuat konsumen sadar keberadaan produk/jasa, sampai mulai tertarik mendalami, hingga akhirnya timbul rasa ingin untuk merasakan, dan akhirnya tindakannya adalah membeli produk atau jasa. Begitulah konsep klasik marketing funnel.
Tapi pada 2012, pakar marketing Philip Kotler menambahkan satu tingkatan dari marketing funnel. Tahapan itu adalah advocacy. Jadi setelah konsumen membeli, mereka kemudian memberi advokasi pada produk/jasa. Advokasi bisa berbentuk rekomendasi, ulasan, atau gambaran mereka atas produk atau jasa.
Walhasil foto yang diunggah usai main padel bisa menjadi salah satu bentuk advokasi. Apalagi dengan takarir semisal, "good game", "seru", "olahraga sambil ngumpul". Advokasi itulah yang menciptakan multiplier effect bagi pengikut mereka di media sosial.
Sehingga pengikut yang melihat foto 'ritual padel' itu mulai aware, tertarik, menggali lebih dalam, hingga memutuskan bermain. Selesai bermain, si pengikut itu berfoto dan memberi advokasi baru. Siklus pun terus berputar. Hingga akhirnya padel pun jadi tren olahraga plus sosial di kota-kota besar.
Konsep marketing funnel ini sejatinya juga terjadi di bidang politik. Strategi advokasi telah diterapkan dalam propaganda komunis dalam menjerat konstituennya. Di era 1950-an, PKI telah melancarkan strategi pemasaran berantai, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Arbi Sanit, 2000).
Strateginya adalah dengan memanfaatkan isu atau kegiatan yang sedang populer di wilayah sasaran sebagai pancingan. Misalnya saat ada musim layangan, PKI menggelar program bagi-bagi layangan.
Berkat strateginya, PKI sukses membentuk kesan ke tiap individu yang jadi sasaran. Simpatisan yang terjerat ide komunis memberi advokasi kepada lingkungannya tentang ide komunis. Hingga akhirnya komunisme sempat mewabah di akar rumput.
Jika dahulu lewat layangan, apakah jika komunis masih eksis kini mereka akan jadikan padel bagian propagandanya? Yang jelas saya baru melihat PKB yang mulai menjadikan padel sebagai bagian dari gimmick politik. Gimmick yang unik pula. Sebab partai santri ternyata sudah tak bermain bola, tapi bermain padel!
Sulit rasanya membayangkan ada komunis atau aktivis kiri bermain padel. Karena padel jadi simbol kelas sosial atas. Padel pun jadi salah satu bisnis paling menarik bagi pemilik modal alias kapitalis. Dengan tren yang terus mewabah, kita masih akan melihat banyak tanah kosong yang beralih jadi tempat nongkrong alias bermain padel.
Walhasil tak mengagetkan saat ada tanah yang saat Idul Adha Juni lalu menjadi lokasi jualan kambing dan sapi, kini sudah menjadi lokasi kalangan elite Jakarta bermain padel.
Lantas apakah tren padel dari kaca mata bisnis bisa bertahan lama? Pertanyaan ini bisa dijawab sederhana lewat teori keseimbangan ekonomi. Hal yang berarti tren pedel masih akan menggiurkan secara bisnis selama jumlah peminat lebih tinggi dibanding jumlah lapangan. Karena itu jadi penting bagi pemilik bisnis agar olahraga ini tetap menjadi tren yang bergulir.
Sebaliknya jika jumlah lapangan yang ada ternyata melebihi peminat, maka titik balik tren padel muncul. Dalam kondisi ini akan banyak lapangan padel kosong dan secara optik menjadi advokasi yang berbalik negatif. Bisnis padel pun jadi berisiko seumur jagung.
Tapi kembali ke judul artikel ini, saya secara random membayangkan apakah mungkin ada penganut komunis bermain padel? Kerandoman yang tiba-tiba muncul usai melihat di sosial media seorang artis sedang bermain padel dengan atribut dari kaki hingga kepala menggunakan jenama kapitalis.
Plus lapangan padel yang tampak disponsori perusahaan berkapital raksasa. Perusahaan yang dalam teori nilai lebih Karl Marx disebut cenderung mengeksploitasi ketimbang membayar buruh sesuai upah nilai kerjanya.
Tapi dengan segala kapitalistiknya olahraga ini bukan tak mungkin banyak penganut ideologi komunis yang kini jadi padel mania. Karena mengutip Daniel Bell lewat judul bukunya The End of Ideology (1962) bahwa ideologi telah berakhir. Seperti Bell yang mengaku seorang sosialis di bidang ekonomi, liberal secara politik, tapi konservatif di bidang budaya. Jadi bisa saja ada di belahan negara lain ada seorang yang 'komunis' politiknya tapi padel olahraganya.
(miq/miq)

 6 hours ago
1
6 hours ago
1