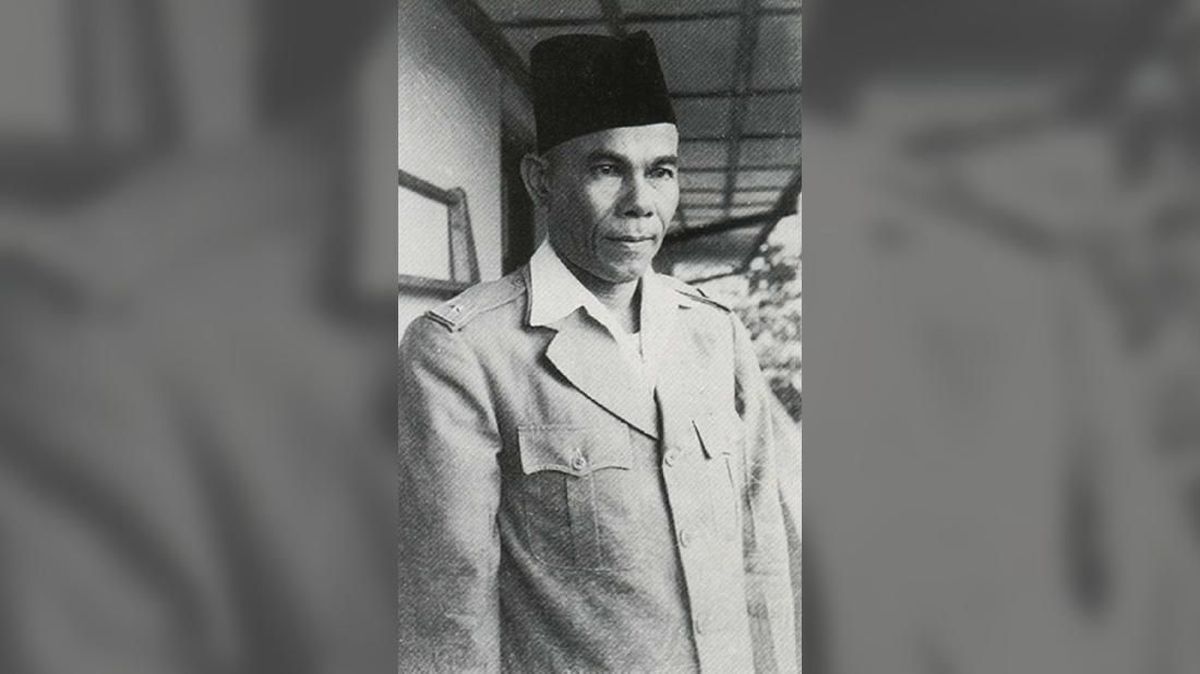Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Nyala api di puncak flare stack kawasan industri Bontang terlihat samar ketika pagi tiba di langit Kalimantan Timur. Namun di balik semburatnya yang tenang, tersimpan pesan bahwa Indonesia belum selesai dalam babak industrialisasi energi.
Dengan kapasitas 660 ribu ton per tahun, pabrik metanol PT Kaltim Methanol Industri kembali beroperasi setelah revitalisasi panjang. Meski begitu, produksi sebesar itu belum mampu mengurangi ketergantungan struktural Indonesia pada metanol impor.
Dalam satu bulan saja, pada Mei 2024, Indonesia tercatat mengimpor 76 ribu ton metanol, meningkat 83% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya-bahkan ketika nilai tukar rupiah menyentuh Rp17.000 per dolar AS.
Di tengah kelebihan pasokan sumber daya energi primer seperti batu bara, gas alam, dan potensi energi terbarukan, fakta bahwa Indonesia masih harus bergantung pada metanol impor menunjukkan ada simpul industri yang belum tersambung. Metanol, yang menjadi bahan baku krusial bagi sektor kimia, energi, dan transportasi maritim, bukan hanya soal molekul kimia, tetapi simbol dari ketahanan pasokan dan posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, pemerintah menetapkan kewajiban bagi pemegang izin tambang batu bara untuk terintegrasi dengan fasilitas pengolahan, termasuk gasifikasi menjadi metanol.
Regulasi ini merupakan revisi penting atas aturan pertambangan tahun 2021, dan menandai babak baru dalam dorongan hilirisasi. Dalam peraturan tersebut, tersedia berbagai insentif fiskal: mulai dari pembebasan PPN, percepatan depresiasi aset, hingga potongan royalti sampai 50% untuk pionir proyek.
Namun kebijakan ini belum sepenuhnya menciptakan kepastian usaha. Skema harga bahan baku yang fluktuatif, ketidakjelasan jaminan offtake produk, dan belum adanya standar karbon nasional membuat investor dan lembaga keuangan masih menghitung risiko regulasi dalam struktur pembiayaannya.
Padahal, dalam konteks ekonomi global yang semakin menuntut jejak karbon rendah dan kepastian rantai pasok, kekosongan kebijakan semacam ini dapat menjadi penentu apakah proyek hilirisasi berjalan atau tertunda.
Di tengah ketidakpastian itu, beberapa inisiatif telah bergulir. Di Bengalon, Kalimantan Timur, Bumi Resources menggagas proyek coal-to-methanol senilai US$ 2 miliar dengan target produksi 1,8 juta ton per tahun. Di Bojonegoro, Jawa Timur, pabrik berbasis gas dengan kapasitas 800 ribu ton direncanakan selesai pada tahun 2027.
Sementara itu, Berau Coal sedang menimbang proyek berbasis lignite sebesar 940 ribu ton per tahun. Jika dua dari tiga proyek ini berhasil mencapai tahap operasional, Indonesia bukan hanya menutup defisit impor metanol, tetapi juga memiliki surplus untuk menembus pasar spot Asia.
Secara global, permintaan metanol meningkat pesat. Asia Pasifik menyerap sekitar 60% pasokan dunia, terutama didorong oleh perluasan pabrik methanol-to-olefins di China dan uji coba bensin metanol (M15) di India. Di sektor pelayaran, ratusan kapal niaga baru kini menggunakan metanol sebagai bahan bakar alternatif.
Singapura telah merespons tren ini dengan menerbitkan Technical Reference 129, standar keselamatan transfer antarkapal untuk metanol, dan menargetkan impor setidaknya satu juta ton metanol rendah karbon per tahun sebelum 2030.
Indonesia memiliki modal kuat untuk masuk dalam arus tersebut. Pertama, sumber daya. Flare gas di Mahakam, Sumatra Selatan, dan Natuna masih belum dimonetisasi secara optimal. Di darat, cadangan 33 miliar ton batu bara kalori rendah menjadi sumber syngas yang stabil dan murah.
Kedua, posisi geografis Indonesia yang strategis memotong waktu tempuh kapal menuju pasar utama seperti Singapura dan Jepang. Ketiga, adanya pipeline proyek energi bersih seperti geothermal dan surya membuka jalan bagi produksi green methanol, yang semakin dibutuhkan di pasar ekspor.
Namun tiga tantangan utama belum terpecahkan: akses pembiayaan, sertifikasi karbon, dan kesiapan infrastruktur. Bank komersial semakin ketat menyalurkan kredit untuk proyek batu bara, kecuali jika disertai sistem penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS).
Di pasar ekspor, intensitas karbon kini menjadi syarat masuk, dan ketiadaan sistem sertifikasi nasional membuat metanol Indonesia terancam dijual dengan harga diskon. Dari sisi logistik, terminal BBM yang ada belum dirancang untuk menangani metanol yang bersifat higroskopis dan korosif.
Di sinilah pentingnya intervensi kebijakan yang bersifat ringan namun berdampak. Pemerintah dapat mengatur harga bahan baku energi melalui formula berbasis indeks netback ekspor, sehingga menciptakan keseimbangan antara hulu dan hilir.
Sovereign guarantee untuk proyek hilirisasi metanol, seperti yang sudah diberikan pada proyek kilang, dapat menurunkan cost of capital dan mempercepat financial close. Pemerintah juga dapat menyusun peta jalan intensitas karbon secara bertahap, sehingga teknologi rendah emisi seperti CCS masuk dalam desain proyek sejak awal.
Dalam jangka menengah, memasukkan fasilitas logistik metanol ke dalam skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPBU) akan mempercepat pembangunan pelabuhan baru yang mampu menangani metanol, amonia, dan bahkan CO₂ cair-tanpa duplikasi investasi dan dengan standar keselamatan yang seragam.
Potensi ekonomi dari langkah ini sangat besar. Impor metanol dan produk turunannya telah menguras devisa lebih dari US$ 700 juta per tahun. Jika Indonesia dapat mengubah batu bara kalori rendah dan gas buang menjadi energi cair rendah karbon, maka bukan hanya devisa yang bisa ditahan, tetapi peluang ekspor baru pun terbuka, lengkap dengan insentif karbon dari sektor pelayaran internasional.
Keberhasilan hilirisasi nikel telah membuktikan bahwa Indonesia mampu menempati posisi sebagai pengatur harga global. Metanol dapat menjadi sektor strategis kedua, kali ini menyasar transisi iklim dan logistik maritim.
Momentum sudah di depan mata. Bila Indonesia mampu mengonsolidasikan regulasi, infrastruktur, dan pasar dalam tiga hingga lima tahun ke depan, kita tak sekadar berhenti sebagai importir, melainkan naik kelas sebagai pemimpin energi bersih di Asia.
(miq/miq)

 7 hours ago
2
7 hours ago
2