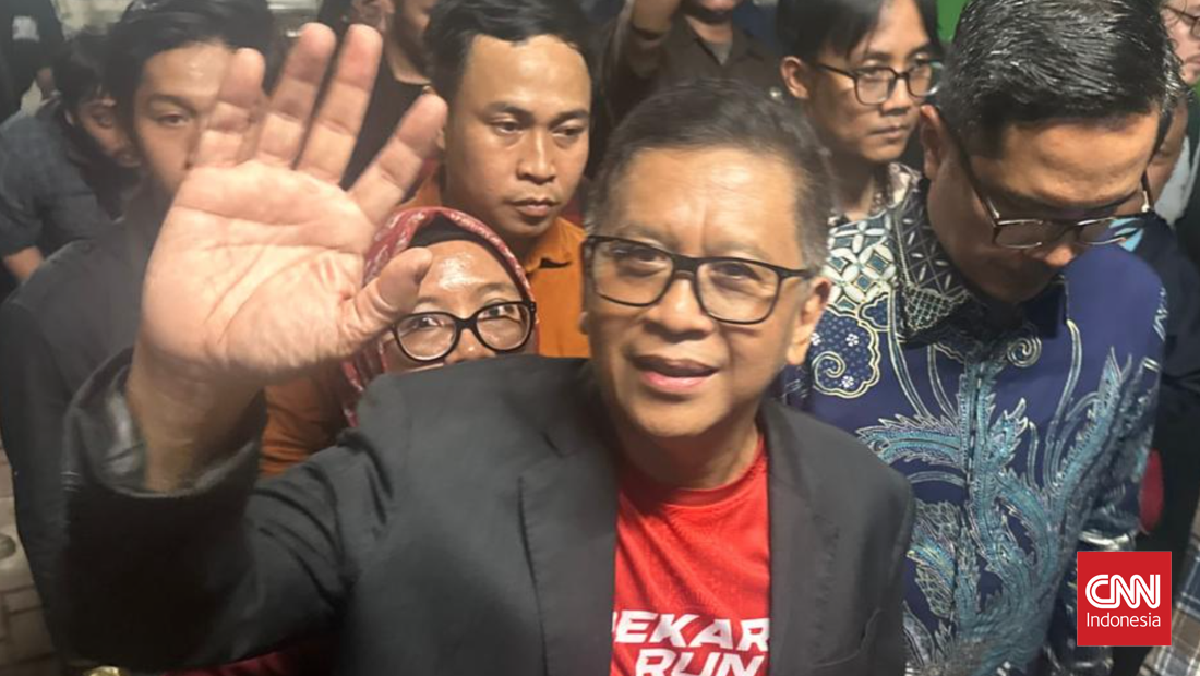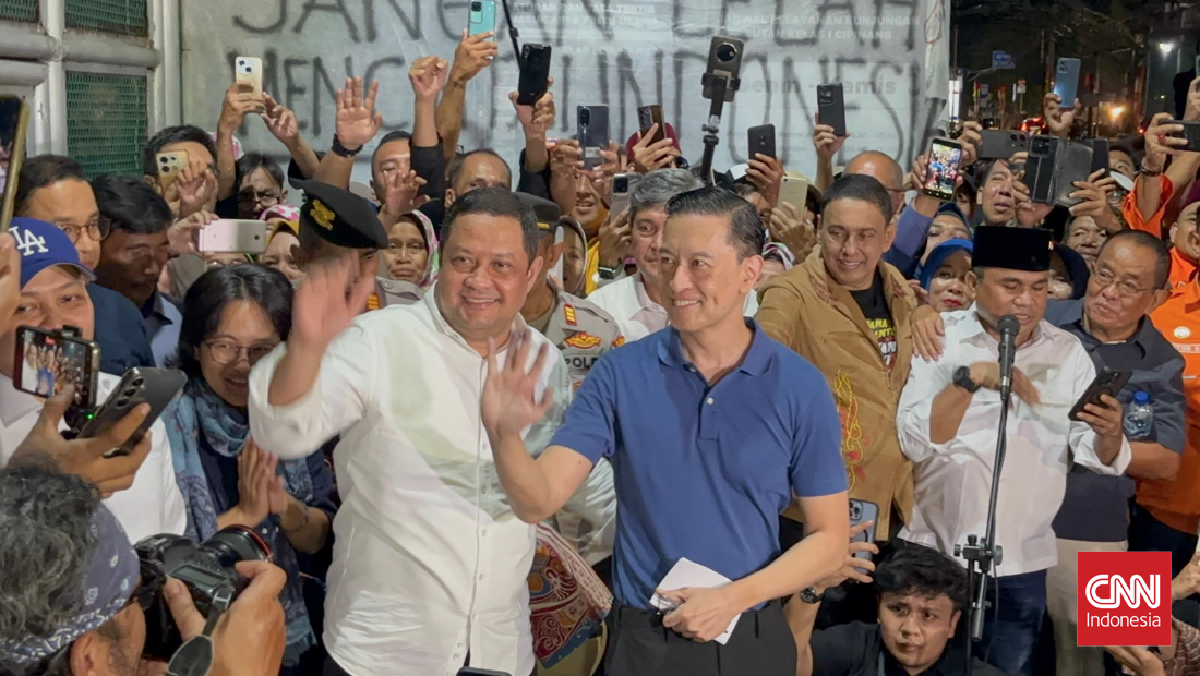Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Indonesia sedang menghadapi tekanan ganda: target penurunan emisi yang kian ambisius dan penurunan produksi minyak nasional yang sulit dibendung. Dalam konteks ini, pemerintah membuka kembali peluang pengelolaan sumur marginal, termasuk sumur tua dan sumur rakyat yang selama ini terabaikan.
Langkah ini dipayungi dasar hukum, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas. Regulasi tersebut memberi ruang legal bagi BUMD, koperasi, dan pelaku UMKM untuk terjun langsung ke lapangan dengan syarat menjaga implementasi beberapa aspek kunci, di antaranya adalah tata kelola, keselamatan, dan sustainability.
Potensi ekonomi dari inisiatif ini tidak kecil. Survei internal menunjukkan bahwa sumur tua di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan dapat menghasilkan tambahan 10.000-15.000 barel minyak per hari. Sebagian besar sumur ini berada di daerah pedesaan dengan akses ekonomi terbatas.
Keterlibatan koperasi dapat memastikan nilai ekonomi kembali ke masyarakat lokal, sebagaimana yang terjadi di India melalui kebijakan Discovered Small Field. Di Distrik Cambay, koperasi petani yang berkolaborasi dengan perusahaan energi berhasil meningkatkan produksi sekaligus mendanai beasiswa dan pembangunan irigasi.
Dampak fiskalnya juga signifikan. Pemerintah daerah memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sementara pemerintah pusat mendapatkan royalti dan pajak penghasilan.
Pengalaman Nigeria menunjukkan lonjakan penerimaan ketika kilang modular memanfaatkan minyak dari sumur tua. Lebih jauh, transparansi penjualan minyak melalui mekanisme resmi akan memperkuat neraca energi nasional dan meningkatkan kredibilitas Indonesia di forum iklim internasional yang kini menuntut data emisi terverifikasi.
Selain itu, revitalisasi sumur tua menciptakan lapangan kerja lokal yang berlapis. Sebuah kilang mini berkapasitas 6.000 barel per hari di Delta Niger, Nigeria, mampu menyerap hingga 250 tenaga kerja langsung dan tidak langsung.
Amerika Serikat juga membuktikan keberlanjutan ribuan sumur berproduksi kecil dengan menggunakan skema penelitian bersama universitas dan Departemen Energi. Di Indonesia, pendekatan kolaboratif ini dapat menahan laju urbanisasi, sekaligus menumbuhkan rantai pasok UMKM untuk kebutuhan pipa, gasket, dan logistik ringan.
Namun, peluang ini tidak lepas dari risiko lingkungan. Data US Environmental Protection Agency mencatat 60 persen emisi metana hulu dihasilkan oleh sumur kecil. Kanada bahkan menghabiskan lebih dari 1,7 miliar dolar Kanada atau sekitar Rp20,264 triliun, untuk menutup sumur marginal yang ditinggalkan.
Tanpa pengelolaan dana penutupan sejak awal, Indonesia berisiko menghadapi beban fiskal serupa. Nigeria pun memberi pelajaran berharga: ketidaktransparanan pembagian keuntungan memicu konflik sosial dan sabotase infrastruktur.
Agar manfaatnya tidak berubah menjadi beban, enam pilar keberlanjutan perlu ditegakkan. Pertama, studi lingkungan yang lengkap wajib diselesaikan sebelum izin diterbitkan, termasuk pemantauan kebocoran metana dengan drone dan citra satelit.
Kedua, kontrak koperasi harus menyisihkan minimal 10 persen pendapatan ke rekening escrow sebagai dana penutupan dan reklamasi, meniru Texas Oil and Gas Regulation and Cleanup Fund. Ketiga, seluruh penjualan minyak wajib tercatat dalam platform digital terverifikasi sehingga masyarakat dapat memantau aliran dana secara real time.
Keempat, koperasi harus bermitra dengan BUMD energi atau Pertamina EP untuk transfer teknologi, mulai dari pompa angguk hemat energi hingga chemical enhanced oil recovery yang dapat meningkatkan faktor perolehan hingga delapan persen.
Kelima, forum musyawarah rutin perlu melibatkan tokoh adat dan pemuda guna mencegah eskalasi konflik sosial. Keenam, insentif fiskal harus berbasis kinerja, diperpanjang hanya jika target penurunan emisi dan penyerapan tenaga kerja tercapai.
Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah. BUMD dapat menjadi tulang punggung yang memfasilitasi perizinan, penyediaan jaringan pipa, dan akses pasar.
Jika BUMD kekurangan modal, bank pembangunan daerah dapat menerbitkan obligasi hijau dengan jaminan pendapatan sumur tua. Model serupa telah sukses di Kolombia untuk proyek air bersih. Keterlibatan UMKM akan memperluas efek berganda ekonomi lokal.
Indonesia memiliki modal sosial yang jarang dimiliki negara produsen minyak lain: tradisi gotong royong. Pola koperasi yang berbasis kebersamaan dapat menekan biaya pengawasan dan memastikan keberlanjutan. Pengetahuan lokal dari kelompok pengeboran rakyat di Cepu tentang pengendalian tekanan dan pencampuran lumpur perlu terdokumentasi agar menjadi panduan keselamatan resmi.
Peraturan Menteri ESDM No. 14/2025 membuka "jendela kesempatan" bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menampilkan tata kelola migas yang selaras dengan prinsip ESG. Dunia sedang mendesak pengurangan emisi, sementara kebutuhan energi domestik tetap tinggi.
Revitalisasi sumur tua dapat menjadi bentuk circular hydrocarbon economy yang mengoptimalkan cadangan yang ada tanpa membuka lahan baru dan tanpa memperparah dampak lingkungan.
Pemerintah pusat kini telah menyediakan kerangka hukum, kini pelaksanaannya menjadi kunci. Gubernur, bupati, BUMD, koperasi, dan UMKM perlu bergerak serentak untuk memastikan sumur-sumur senja ini tidak hanya menambah lifting nasional, tetapi juga membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pengelolaan migas di era transisi energi bisa tetap produktif, transparan, dan ramah lingkungan. Kesempatan ini tidak hanya soal energi, tetapi juga bisa meningkatkan reputasi bangsa yang mampu merawat warisan masa lalu untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
(miq/miq)

 22 hours ago
3
22 hours ago
3