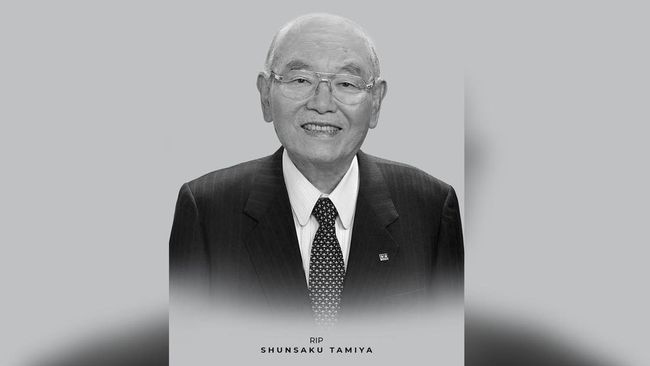Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Tidak ada organisasi publik yang benar-benar kebal dari krisis. Krisis tidak mengenal batas administratif. Ia bisa muncul di mana saja: kota besar, kabupaten kecil, bahkan desa terpencil. Namun di tengah keragaman tantangan daerah, Jakarta menyimpan pelajaran penting-bahwa kemauan untuk bersikap antisipatif adalah prasyarat utama dalam tata kelola pemerintahan modern.
Dalam pelatihan komunikasi krisis yang diselenggarakan BPSDM DKI Jakarta, penulis berkesempatan melihat dari dekat upaya serius dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tidak lagi sekadar menjadi "pemadam kebakaran". Mereka berusaha mengenali pola krisis dari hulu, memperbaiki komunikasi dari dalam, dan memetakan potensi gangguan publik jauh sebelum terjadi.
Kota megapolitan seperti Jakarta menyimpan sejumlah persoalan seperti kemacetan, kesenjangan, padatnya harapan warga, dan derasnya dinamika digital. Di saat banyak daerah masih "menunggu bola panas datang" sebelum menyiapkan narasi, Jakarta mulai menggeser cara pandang: krisis bukan hanya soal kesiapan merespons, tapi juga soal kemauan untuk mendahului.
Di sejumlah daerah, krisis seringkali baru disadari setelah menjadi polemik nasional. Situasi ini berulang dalam isu-isu seperti penanganan banjir, konflik agraria, layanan pendidikan, bahkan urusan sederhana seperti pembuatan administrasi kependudukan.
Namun, yang perlu digarisbawahi adalah: krisis tidak selalu destruktif. Ia juga dapat menjadi momen pembelajaran dan pembentukan karakter kelembagaan. Dalam perspektif konstruktifis, krisis adalah ruang tumbuh-proses pembentukan makna baru, praktik baru, dan relasi baru antara pemerintah dan masyarakat.
Dari Inovasi hingga Kontroversi, Krisis Pemerintah Daerah
Pengalaman Jakarta menunjukkan bahwa tidak ada krisis yang "terlalu sepele" untuk diabaikan. Setiap potensi gangguan terhadap kepercayaan publik perlu dikelola secara sadar. Bahkan sebuah antrean panjang di loket pelayanan bisa menjadi "krisis mini" jika tidak dijelaskan, tidak disapa, tidak dihadapi dengan empati.
Jakarta tidak kekurangan contoh kasus. Di Dinas Kesehatan, misalnya, ketika Puskesmas Kembangan ditunjuk sebagai pilot project pelepasan nyamuk Wolbachia-sebuah inovasi yang menanamkan bakteri baik ke nyamuk Aedes aegypti untuk menekan penularan DBD-reaksi masyarakat tidak selalu seragam.
Sebagian menerima, sebagian ragu. Bagi warga yang tidak familiar dengan pendekatan biologis semacam ini, pelepasan nyamuk justru dipersepsikan sebagai "ancaman baru". Jika dibiarkan tanpa komunikasi yang terencana, intervensi inovatif ini bisa berubah menjadi krisis sosial.
Kita bisa menyalahkan kurangnya literasi masyarakat. Tapi pendekatan konstruktifis justru menantang kita untuk membalik pertanyaan: sejauh mana pemerintah berikhtiar secara terus menerus membentuk ruang pemahaman bersama? Komunikasi tidak boleh dimaknai sebagai aktivitas linier dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi adalah tindakan dialogis, sebuah upaya membangun makna secara kolaboratif, agar kebijakan tidak hanya dipahami-tetapi juga dimiliki oleh publik.
Begitu pula saat terjadi kemacetan digital di DPMPTSP akibat lonjakan permintaan layanan. Protes warga meluas, pelayanan tersendat, kepercayaan goyah. Namun jika ASN dilatih untuk memaknai krisis sebagai ruang negosiasi ulang peran, maka krisis ini bisa diubah menjadi peluang membangun kredibilitas baru. Alih-alih defensif, komunikasi yang terbuka dan penuh empati akan memberi sinyal bahwa pemerintah hadir, mendengar, dan belajar.
Ada lagi, krisis sistem PPDB di Dinas Pendidikan juga menyimpan potensi pembelajaran serupa. Saat sistem penerimaan siswa baru berbasis zonasi menimbulkan kerumitan teknis dan emosi sosial, kepala sekolah dan pejabat dinas kerap kali menjadi sasaran kekesalan orang tua.
Dalam konteks ini, kehadiran komunikasi krisis yang kuat tidak hanya untuk menjelaskan teknis. Ia juga menjadi sarana untuk mendamaikan logika sistem dengan logika kemanusiaan-menghubungkan kebijakan dengan nilai keadilan yang hidup dalam kesadaran publik.
Terakhir, Dinas Lingkungan Hidup menghadapi dinamika yang berbeda, namun tetap berada dalam spektrum krisis yang memerlukan respons reflektif. Pascaevent besar seperti malam tahun baru atau Idul Fitri, sampah menumpuk dan opini publik mudah terbakar.
Tantangan komunikasi di sini bukan sekadar klarifikasi teknis, tetapi juga mengajak publik untuk berpartisipasi dalam solusi. Komunikasi yang dialogis, partisipatoris, dan menyentuh nilai kolektif akan jauh lebih kuat publicral sekadar penjelasan publicral.
Dalam seluruh contoh ini, kita melihat bahwa krisis bukan sekadar fakta objektif. Ia adalah hasil interaksi antara kejadian, ekspektasi publik, dan bagaimana organisasi merespons secara simbolik. Dengan kata lain, krisis adalah peristiwa sosial yang bisa dibentuk ulang lewat komunikasi.
Membentuk Makna di Tengah Krisis
Jakarta memang memiliki keunggulan dari sisi anggaran dan akses terhadap sumber daya. Namun bukan berarti daerah lain tidak bisa meniru pendekatannya. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melakukan pemetaan risiko, membuka kanal dialog warga, dan menjadikan komunikasi sebagai bagian dari sistem deteksi dini.
Itulah mengapa pendekatan konstruktifis menjadi sangat relevan dalam pengelolaan komunikasi krisis. Komunikasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai strategi "menjinakkan" krisis. Ia harus menjadi medium untuk membangun kepercayaan secara otentik. Dalam konteks birokrasi Jakarta, komunikasi krisis adalah alat kepemimpinan moral dan kultural, bukan hanya alat teknis manajemen.
Krisis, jika dilihat secara konstruktif, justru memberi kesempatan bagi pemerintah untuk menampilkan wajah terbaiknya: sebagai institusi yang belajar, merespons dengan hati, dan berani meminta maaf jika perlu.
Krisis selalu datang dalam tahapan. William T. Coombs, tokoh terkemuka komunikasi krisis, menggambarkan lima fase krisis: emerging (kemunculan gejala), prodromal (tanda-tanda krisis mulai terlihat), acute (krisis pecah), chronic (fase dampak berkepanjangan), dan resolution (pemulihan dan pembelajaran). Namun pendekatan konstruktifis menambahkan satu hal penting: proses konstruksi makna sepanjang krisis berlangsung.
ASN Bukan Sekadar Pelaksana, Tapi Komunikator Publik
Di setiap fase, organisasi perlu mendengarkan bukan untuk membantah, tetapi untuk memahami. Respons bukan sekadar menenangkan, tapi menjembatani makna. Inilah yang harus menjadi kesadaran baru ASN: menjadi komunikator bukan hanya untuk menjaga reputasi, tetapi untuk membangun relasi baru dengan masyarakat, berbasis kepercayaan dan nilai bersama.
Pemahaman tentang komunikasi krisis yang telah dilakukan harus terus dikembangkan secara sistematis, lintas jenjang, dan lintas disiplin. Harus ada integrasi antara pembelajaran teknis dengan pendekatan reflektif.
ASN harus diberikan ruang untuk memahami dirinya sebagai aktor dalam ekosistem sosial, bukan sekadar pelaksana teknis regulasi. Diperlukan ruang praktik, simulasi kasus, refleksi kritis, dan diskusi interaktif agar pelatihan tidak menjadi "ceramah", tetapi pengalaman belajar yang hidup.
Kota Jakarta terlalu penting untuk dikelola hanya dengan pendekatan prosedural. Kota ini membutuhkan ASN yang mampu merespons situasi kompleks dengan sensitivitas sosial dan keterampilan komunikasi yang matang. Sebab setiap krisis yang terjadi bukan hanya soal rusaknya sistem, tetapi juga ujian atas relasi pemerintah dan warganya.
Krisis memang tidak bisa dihindari. Namun jika dikelola dengan pendekatan konstruktif, krisis bisa menjadi energi perbaikan, sumber legitimasi baru, dan panggung kepemimpinan yang bermakna. ASN Jakarta hari ini tidak cukup hanya cakap birokrasi. Mereka harus menjadi komunikator yang reflektif, adaptif, dan berani membentuk makna bersama dengan publik.
Krisis adalah titik balik. Ia bisa menjadi awal kehancuran, atau justru menjadi awal kepercayaan baru-tergantung bagaimana ia dikelola. Pemerintah daerah, dari Aceh hingga Papua, dari kota hingga kabupaten, harus menyadari bahwa komunikasi adalah alat kendali, bukan sekadar alat klarifikasi.
Jakarta sudah memulai. Kini saatnya daerah lain belajar, meniru, dan menyesuaikan. Karena masa depan pemerintahan bukan hanya milik mereka yang cepat bekerja, tetapi juga milik mereka yang cepat membaca tanda-tanda perubahan. Dan tanda-tanda itu, seringkali, muncul lewat bisikan krisis yang datang perlahan.
(miq/miq)

 9 hours ago
3
9 hours ago
3