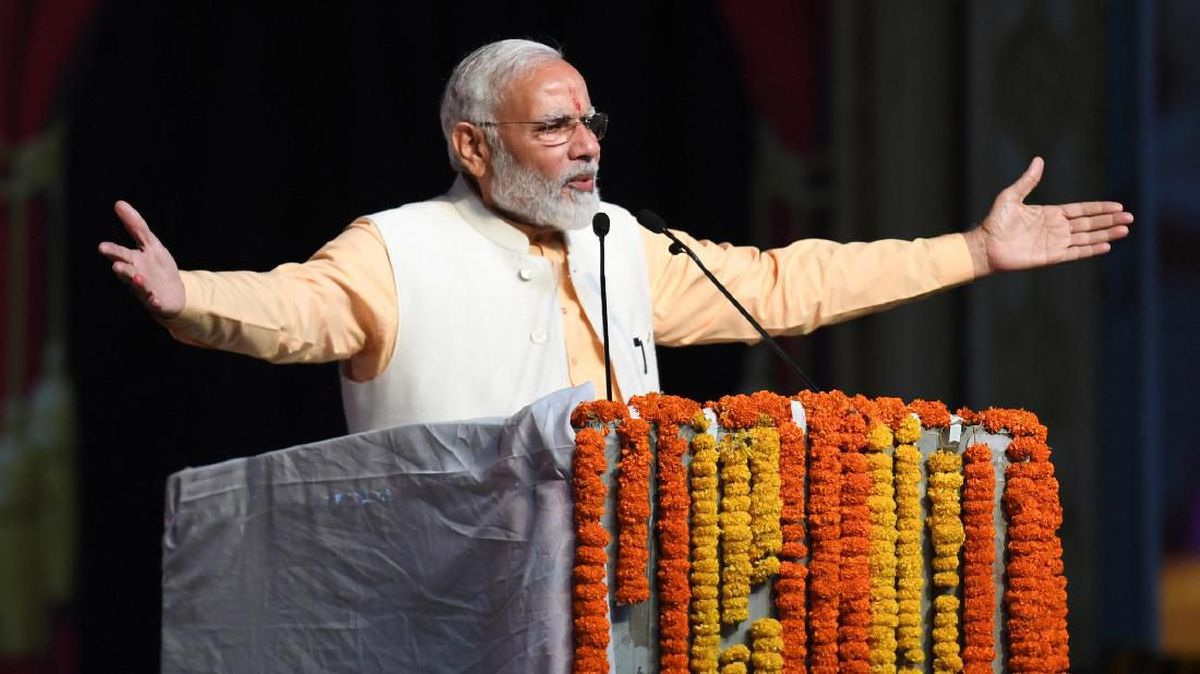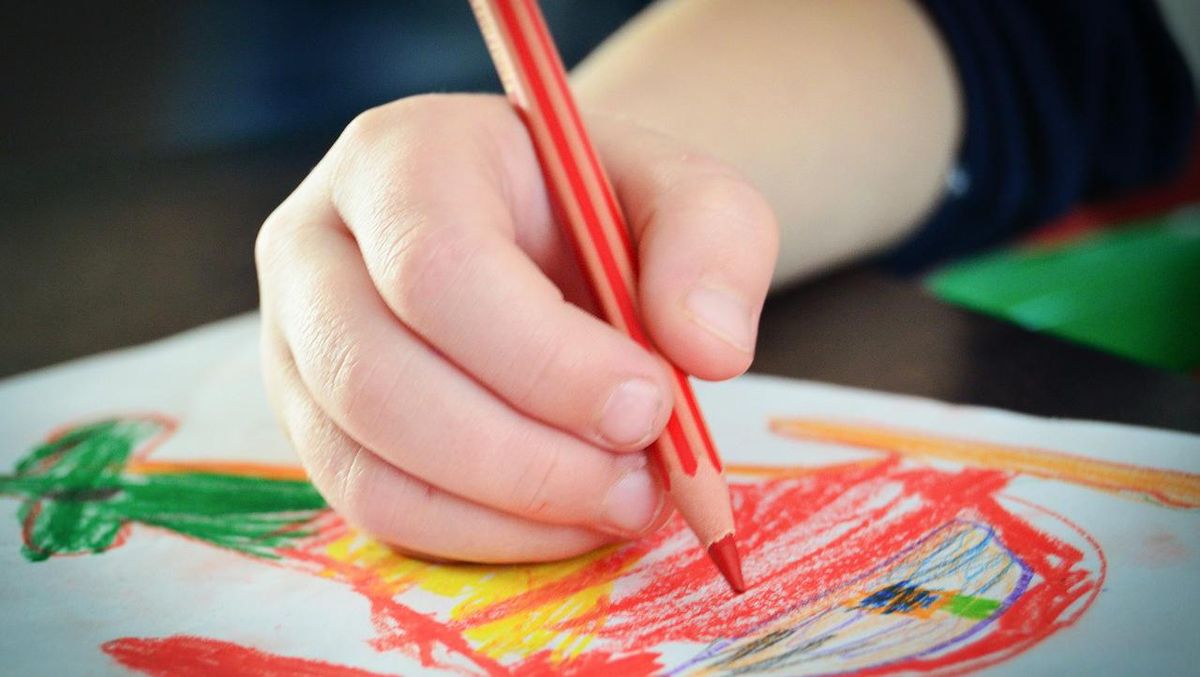Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Jika ditarik ke belakang, agenda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) kini kian mendekati tahap implementasi setelah melalui rangkaian proses yang panjang. Tonggak pentingnya ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menjadi landasan hukum utama.
Kehadiran regulasi ini tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga menjadi pijakan yuridis dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, serta pengaturan kelembagaan yang mengatur pembangunan sekaligus penyelenggaraan pemerintahan di kawasan ibu kota baru.
Dalam opini saya yang dimuat di Kompas.com pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan judul "Keppres IKN dan Status Ibu Kota Negara," saya juga menguraikan sejumlah catatan yang hingga kini masih menjadi bahan diskursus para teknokrat dan akademisi. Dari sudut pandang hukum ketatanegaraan, perdebatan utama terletak pada kepastian waktu penetapan keputusan presiden mengenai IKN dan status IKN.
Pertanyaan yuridis yang muncul adalah apakah keppres tersebut akan ditetapkan pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari legacy politiknya, ataukah justru akan menjadi kewenangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isu ini penting, sebab menyangkut konsistensi asas kesinambungan pemerintahan, kepastian hukum dalam transisi kekuasaan, serta legitimasi formil dari status kelembagaan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
Berkaca dari Rencana Jangka Panjang Pembangunan IKN, terdapat 4 (empat) tahapan yang dibagi secara tegas yaitu: 2022-2024 sebagai tahap pemindahan awal, 2025-2029 sebagai tahap kedua yaitu membangun IKN sebagai daerah inti yang tangguh.
Kemudian 2030-2034 sebagai tahap ketiga yaitu melanjutkan pembangunan IKN lebih progresif, 2035-2039 sebagai tahap keempat membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota percepatan untuk pembangunan Kalimantan, 2040-2045 sebagai tahap memperkokoh reputasi kota dunia untuk semua. (Antara News, 13/8/2024)
Setelah menyelesaikan fase awal yang sarat dengan pembangunan infrastruktur dasar dan landmark pemerintahan inti, megaproyek ini bersiap melangkah ke tahap kedua pada periode 2025-2029. Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap ini, difokuskan pada penyelesaian kompleks legislatif dan yudikatif, pengembangan ekosistem pendukung, serta pembukaan akses menuju wilayah perencanaan (WP) 2. (Investor Daily, 17/4/2025).
Berdasarkan data Otorita IKN, pembangunan IKN tahap pertama telah mencapai progres fisik 98,2 persen per 12 Februari 2025 meliputi pembangunan sarana utama seperti Istana Presiden, perkantoran, dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta pembangunan infrastruktur dasar mencakup infrastruktur penyediaan air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah untuk penduduk pionir. (Perpres 63/2022).
Progres pembangunan IKN menunjukkan capaian yang signifikan dan hampir mendekati target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tentu perlu terus diiringi dengan peningkatan kualitas agar hasil pembangunan benar-benar optimal.
Dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyajikan hasil pemeriksaan atas kinerja pembangunan IKN Tahun Anggaran 2022 hingga Triwulan III 2023 sebagai bagian dari tahap pertama pembangunan 2022-2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama instansi terkait.
Selain itu, disebutkan bahwa perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana. Persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai.
Di antaranya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 hektare dari 36.150 hektare tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya Hak Pengelolaan Lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas lima area hasil pengadaan tanah. (Kompas.com, 14/6/2024)
Laporan ini memberikan sejumlah catatan yang konstruktif, antara lain perlunya penyesuaian lebih lanjut agar pembangunan infrastruktur IKN semakin selaras dengan arah RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, serta Rencana Induk IKN. Catatan tersebut dapat menjadi masukan penting untuk memastikan proses pembangunan tidak hanya berorientasi pada percepatan, tetapi juga pada keberlanjutan, konsistensi perencanaan, dan kualitas hasil akhir.
Hal tersebut juga senada dengan penelitian Daron Acemoglu & James A. Robinson yang berjudul: "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty," bahwa perencanaan institusi yang lemah dan kebijakan yang disfungsional membuka ruang lebar bagi korupsi dan patronase. Maka, sebagaimana yang dijelaskan oleh MM Gibran Sesunan bahwa pembangunan infrastruktur boleh besar-besaran, tetapi tidak boleh ugal-ugalan. (Harian Kompas, 3/12/2024)
Setelah menyelesaikan fase awal yang sarat dengan pembangunan infrastruktur dasar dan landmark pemerintahan inti, megaproyek ini bersiap melangkah ke tahap kedua pada periode 2025-2029. Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap ini, difokuskan pada penyelesaian kompleks legislatif dan yudikatif, pengembangan ekosistem pendukung, serta pembukaan akses menuju wilayah perencanaan (WP) 2. (Investor Daily, 17/4/2025)
Pascaterbitnya Perpres 79/2025
Bicara soal pembangunan IKN, saya teringat kembali opini saya yang dimuat di Investor Daily, 29 April 2025, berjudul: "Pembangunan IKN: Sinkronisasi Fiskal, Regulasi, dan Political Will." Dalam tulisan tersebut, saya menekankan bahwa tahap kedua pembangunan IKN tidak cukup hanya berbicara mengenai pendanaan. Lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah sinkronisasi fiskal, penguatan regulasi, serta komitmen politik yang konkret dan konsisten.
Tanpa kepastian hukum, transparansi perizinan, dan tata kelola yang antikorupsi, IKN akan kesulitan menarik investasi jangka panjang. Bahkan, tanpa dukungan politik yang jelas, proyek ini terancam berjalan setengah hati, bahkan melenceng dari masterplan awal. (Nicholas Martua Siagian, Hukum Online, 13/8/2025)
Keputusan strategis mengenai kelanjutan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang merupakan warisan kebijakan Presiden Jokowi, kini memperoleh legitimasi politik baru melalui Presiden Prabowo. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang secara eksplisit menetapkan bahwa proses perencanaan, pembangunan kawasan, dan pemindahan fungsi ibu kota diarahkan untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Dari perspektif perencanaan pembangunan, perpres tersebut memuat sejumlah indikator kinerja utama yang bersifat kuantitatif dan terukur, dengan horizon waktu tiga tahun ke depan. Pertama, penyelesaian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan lingkungannya yang mencakup luasan 800-850 hektare, sebagai basis kelembagaan pemerintahan. (Perpres 79/2025)
Kedua, tercapainya 20% realisasi pembangunan gedung/perkantoran pemerintahan, yang menunjukkan capaian awal dari built environment institusional. Ketiga, terpenuhinya 50% pembangunan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, yang sekaligus menandai aspek livability kawasan.
Keempat, ketersediaan sarana dan prasarana dasar minimal sebesar 50%, sebagai prasyarat keberlanjutan sistem perkotaan. Kelima, peningkatan indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan hingga mencapai skor 0,74, yang dapat dibaca sebagai ukuran efisiensi mobilitas intra dan antarwilayah. (Perpres 79/2025)
Pemindahan Aparatur Negara
Berdasarkan perpres tersebut, juga diamanatkan secara bertahap ditargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di Nusantara. Kemudian, hingga tahun 2029 jumlahnya diproyeksikan mencapai 9.500 ASN yang ditempatkan di IKN. Artinya, tantangan percepatan pelaksanaan IKN sebagai "Ibu Kota Politik" tidak hanya berbicara infrastruktur fisik, namun juga menyiapkan infrastruktur sosial dalam rangka pemindahan aparatur negara.
Kalau kita analisis secara sederhana, untuk setiap ASN yang dipindahkan, negara harus menanggung berupa tunjangan kemahalan, fasilitas rumah dinas, hingga tunjangan anak dan asisten rumah tangga (ART), sebanyak dua anak dan satu ART per ASN. Biaya ini bukan kecil, dan jika dikalikan ribuan ASN, maka tekanan pada APBN akan semakin terasa berat.
Selain itu, respons Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap agenda pemindahan ke Ibu Kota Nusantara menunjukkan adanya dimensi penting yang perlu dikelola dengan pendekatan kebijakan publik yang adaptif. Beberapa kekhawatiran yang mengemuka di ruang-ruang diskusi informal.
Mulai dari kepastian jalur karier, ketersediaan layanan dasar bagi keluarga, hingga persepsi mengenai keberlanjutan proyek, sebetulnya dapat dipandang sebagai policy feedback yang konstruktif. Hal ini menandakan bahwa transisi menuju ibu kota baru bukan hanya persoalan infrastruktur fisik, melainkan juga transformasi sosial-birokratis yang memerlukan perencanaan matang.
Sebagian ASN di Jakarta telah menikmati ekosistem perkotaan yang relatif mapan, baik dari sisi aksesibilitas layanan publik maupun jaringan sosial. Oleh karena itu, pemindahan ke kawasan baru yang masih dalam tahap pembangunan dapat menjadi tantangan adaptasi. Namun, tantangan tersebut sekaligus membuka peluang untuk merancang tata kelola birokrasi dan layanan dasar yang lebih modern, efisien, serta berbasis pada prinsip smart governance.
Dalam kerangka teknokratik, pemerintah perlu menetapkan strategi transisi ASN yang realistis, bertahap, dan berbasis kebutuhan nyata. Prioritas kebijakan bukan sekadar mempercepat pemindahan secara simbolik, melainkan memastikan adanya jaminan keberlanjutan karier, infrastruktur sosial, dan kualitas hidup yang memadai bagi ASN dan keluarganya.
Dengan demikian, pemindahan ASN ke IKN dapat diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan nasional, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah.
Konsistensi Perencanaan Teknokratik
Berbeda dengan tahap pertama (2022-2024) yang diwarnai dengan intensitas pembangunan dan aliran fiskal yang kuat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, tahap kedua berpotensi menghadapi tantangan koordinasi dan pendanaan yang lebih kompleks, termasuk pascainstruksi efisiensi anggaran, dinamika ekonomi global, hingga fokus anggaran pada program strategis Asta Cita Prabowo Subianto.
Pascaterbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan arah Ibu Kota Nusantara sebagai "Ibu Kota Politik," mekanisme pendanaan idealnya mengikuti mandat Undang-Undang IKN, yaitu tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebaliknya, pembiayaan perlu ditopang melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang membuka ruang kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan mitra internasional. Secara normatif, pendekatan ini memberikan peluang lebih besar bagi partisipasi swasta maupun investor asing untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan memperkuat daya ungkit pembangunan.
Tahap kedua pembangunan IKN tidak semata-mata berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik seperti kantor pemerintahan, perumahan ASN, maupun jaringan jalan tol. Lebih dari itu, agenda strategis yang harus dikedepankan mencakup reformasi sistem perizinan, konsistensi dalam perencanaan pembangunan nasional, penyederhanaan regulasi melalui langkah-langkah deregulasi, serta penguatan mekanisme transparansi.
Tanpa perbaikan tata kelola investasi yang bersifat sistemik, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berpotensi hanya berhenti pada jargon teknokratik tanpa realisasi yang efektif.
Dalam konteks iklim investasi, ketidakpastian regulasi dan kepastian hukum berpotensi menjadi faktor penghambat yang mengurangi minat investor domestik maupun asing untuk turut serta dalam pembiayaan pembangunan IKN.
Oleh karena itu, langkah prioritas pemerintah adalah melakukan konsolidasi regulasi, khususnya antara Undang-Undang IKN dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) serta undang-undang sektoral lainnya. Harmonisasi regulasi ini menjadi krusial guna mencegah tumpang tindih kewenangan maupun alokasi anggaran, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang dapat meningkatkan kredibilitas pembangunan IKN di mata investor.
(miq/miq)

 2 hours ago
2
2 hours ago
2