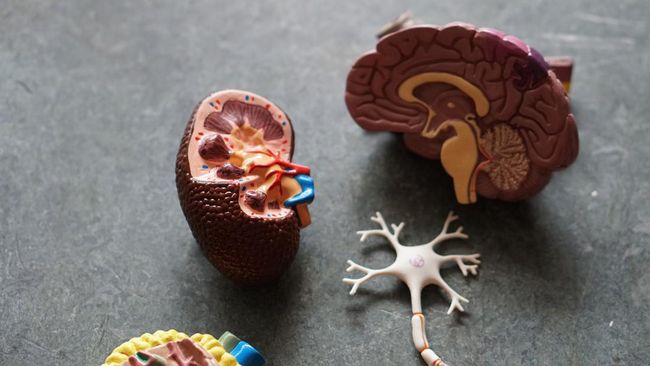Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi, Indonesia perlu memperkuat kemandirian energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya domestik secara optimal. Wacana mandatori bahan bakar nabati (BBN) oleh pemerintah, khususnya etanol 10 persen (E10) pada 2027, kembali memunculkan diskursus nasional tentang pembangunan energi berbasis komoditas pertanian dan perkebunan.
Gagasan ini menyoroti bagaimana komoditas agrikultur seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong tidak hanya berperan sebagai sumber pangan, tetapi juga dapat menjadi pilar energi nasional. Upaya ini bukan semata strategi diversifikasi, melainkan langkah menuju kedaulatan energi serta transformasi menuju ekonomi hijau yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sebagai produsen minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia menyumbang sekitar 58%-60% pasokan global. Komoditas ini berkontribusi 13,5% terhadap pendapatan ekspor nasional dan menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja, menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan di Sumatra dan Kalimantan.
Namun, sekitar 70% produksi CPO Indonesia, masih diekspor dalam bentuk mentah. Padahal, produk turunan dari minyak kelapa sawit seperti biodiesel, bioavtur, oleokimia, dan biogas memiliki nilai tambah 15%-20% lebih tinggi di pasar global. Hilirisasi sawit secara menyeluruh berpotensi menambah 2%-3% terhadap PDB Indonesia dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru.
Kebutuhan untuk memperkuat hilirisasi ini sejalan juga dengan arah komitmen pemerintah terhadap transisi energi terbarukan. Upaya hilirisasi yang mendorong nilai tambah produk kelapa sawit tidak dapat dilepaskan dari agenda nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mempercepat adopsi energi bersih.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Umum ke-80 PBB pada September 2025 menekankan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia telah merasakan langsung dampak perubahan iklim. Hal ini menuntut langkah nyata, bukan sekadar retorika.
Indonesia berkomitmen terhadap Paris Agreement 2015 dan menargetkan pencapaian emisi nol bersih sebelum tahun 2060. Salah satu langkah konkret ialah memperkuat transisi energi nasional dari bahan bakar fosil menuju bahan bakar terbarukan, dengan bahan bakar nabati sebagai salah satu kunci utama.
Program biodiesel di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah menunjukkan kemajuan pesat. Sejak mandatori B5 pada 2006 hingga B35 pada 2024, tingkat pencampuran biodiesel terus meningkat seiring pasokan CPO domestik yang stabil. Realisasi produksi biodiesel nasional pada 2024 mencapai lebih dari 13 juta kiloliter dengan serapan domestik yang meningkat signifikan. Program ini menghemat devisa sekitar US$ 7,86 miliar dan menekan impor solar hampir 40%.
Keberhasilan biodiesel menjadi pijakan penting untuk memperluas pemanfaatan energi hingga ke limbah sawit. Selain biodiesel, hasil sampingan industri sawit seperti cangkang, serat, dan palm oil mill effluent (POME) dapat dikembangkan sebagai sumber energi baru.
Serat dan cangkang dapat diubah menjadi biomassa dan biochar yang bernilai ekonomi, sedangkan POME dapat dimanfaatkan untuk biogas guna membangkitkan listrik sekaligus menjadi land application di kebun sawit serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Jika seluruh potensi biomassa dan POME dimanfaatkan, Indonesia berpeluang menghasilkan lebih dari 2 gigawatt listrik, setara dengan pasokan energi untuk hampir dua juta rumah tangga per tahun.
Meski peluang hilirisasi industri kelapa sawit besar, sejumlah tantangan tetap perlu diatasi. Pertama, pembangunan infrastruktur hilirisasi membutuhkan investasi besar, diperkirakan mencapai US$ 15 miliar, mencakup fasilitas pengolahan, logistik, dan penyimpanan.
Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei menjadi salah satu contoh dengan investasi sekitar Rp 6,5 triliun untuk sektor oleokimia dan biofuel. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi pembiayaan yang tidak hanya bergantung pada subsidi, tetapi juga melibatkan peran swasta, perbankan nasional, dan lembaga keuangan.
Pemerintah dapat memperkuat keberlanjutan fiskal melalui reformasi skema pendanaan, penerbitan green bond, penguatan Dana Transisi Energi Nasional, serta kemitraan publik-swasta agar pembangunan fasilitas hilirisasi berlangsung merata dan berkelanjutan di berbagai daerah.
Kedua, produktivitas kebun kelapa sawit rakyat yang mencakup 40% dari total lahan sawit baru sekitar 2,6 ton CPO per hektare per tahun, jauh di bawah potensi empat ton hingga enam ton. Produktivitas rendah ini berdampak pada pendapatan petani yang stagnan, menurunnya efisiensi rantai pasok, serta tingginya ketergantungan pada harga CPO mentah.
Akibatnya, daya saing perkebunan rakyat menurun dan kontribusinya terhadap pasokan bahan baku biodiesel menjadi terbatas. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi solusi utama untuk meningkatkan hasil dan kualitas CPO. Namun, hingga 2025 realisasinya baru mencapai sekitar 26% dari target nasional. Percepatan PSR memerlukan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, pendampingan teknis berkelanjutan, serta penyediaan benih unggul dan pupuk yang terjamin.
Ketiga, aspek keberlanjutan dan tata kelola masih menjadi pekerjaan besar yang tidak dapat diabaikan. Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), standar nasional wajib, baru mencakup 35,6 persen lahan sawit Indonesia.
Sementara RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), sertifikasi global sukarela, baru mencakup sekitar 2,7 juta hektar atau 19 persen dari total lahan sawit nasional. Artinya, sekitar 45 persen lahan sawit Indonesia belum tersertifikasi baik secara ISPO maupun RSPO.
Sertifikasi penting karena menjamin bahwa produksi sawit memenuhi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Sertifikasi juga membuka akses ke pasar global yang menuntut standar keberlanjutan, terutama dari Uni Eropa. Bagi pemerintah, sertifikasi memperkuat citra Indonesia sebagai produsen minyak sawit yang bertanggung jawab serta mendukung pengurangan emisi dan perlindungan hutan.
Keempat, riset dan inovasi teknologi menjadi faktor penting dalam memperkuat hilirisasi sawit. Pengembangan teknologi bioenergi, digitalisasi rantai pasok untuk keterlacakan, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi harus ditingkatkan untuk menjamin efisiensi dan keberlanjutan produksi.
Peningkatan investasi riset juga diperlukan dalam pengolahan limbah sawit menjadi biofuel generasi kedua agar Indonesia dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar energi terbarukan.
Kebijakan hilirisasi kelapa sawit perlu dipandang bukan semata sebagai proyek ekonomi, melainkan sebagai strategi nasional untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan keberlanjutan lingkungan. Dengan langkah-langkah yang konsisten dan terukur, bertani energi dapat menjadi strategi realistis bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor energi dan mempercepat transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan.
Hilirisasi kelapa sawit yang dikelola dengan baik bukan hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor pertanian sebagai penopang kedaulatan energi nasional.
(miq/miq)

 5 hours ago
1
5 hours ago
1