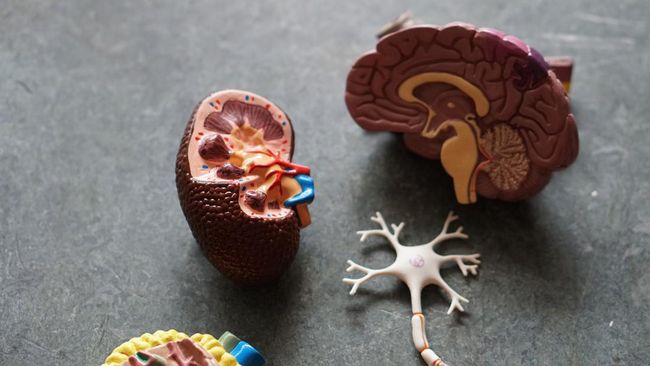Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Asta Cita nomor dua Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang kemandirian energi. Sebuah cita-cita yang pada dasarnya adalah upaya menjaga martabat bangsa. Di era ketika energi menjadi mata uang baru dalam diplomasi global, kemandirian energi bukan lagi soal teknis produksi, melainkan politik pengaruh.
Amanat Paris Agreement menjadi jangkar moral bagi Indonesia untuk melangkah, tetapi bagaimana langkah itu diayunkan akan menentukan posisi Indonesia di antara dua arus besar dunia akhir-akhir ini, yaitu industrialisasi hijau dan perebutan pengaruh ekonomi.
Indonesia menyadari bahwa Energi Baru dan Terbarukan (EBT) bukan sekadar pilihan rasional dalam mitigasi iklim, tetapi juga medan baru bagi soft power. Melalui energi hijau, sebuah negara dapat memperluas pengaruhnya tanpa senjata, tanpa paksaan, melainkan melalui inspirasi, keunggulan moral, dan keteladanan kebijakan.
Namun di balik narasi ideal ini, transisi energi di Indonesia masih berjalan di tempat. Mulai dari persoalan bankability hingga ketimpangan pendanaan. Masalah paling krusial adalah bahwa EBT belum dianggap bankable atau layak didanai oleh bank-bank di Indonesia. Proyek-proyeknya sering gagal meyakinkan lembaga keuangan, bukan karena kurang prospektif, tetapi karena kerangka kebijakan dan risiko ekonomi yang belum tertata.
Ketika pasar belum percaya, narasi kedaulatan energi kehilangan daya pengaruhnya. Padahal, dalam logika soft power, kepercayaan adalah modal utama, baik di tingkat investor, masyarakat, maupun antarnegara.
Di tingkat kawasan, ASEAN sebenarnya telah mencoba membangun kerangka kerja sama energi melalui ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) yang kini memasuki fase II hingga 2025. Namun seperti kebanyakan kebijakan regional, rangka aksi ini masih berhenti di tataran retorika saja, seperti pelatihan dan seminar.
Efektivitasnya terbentur pada masalah klasik, perbedaan kepentingan nasional, tumpang tindih kebijakan, dan lemahnya pendanaan kolektif. Padahal, jika ASEAN ingin relevan di abad energi baru ini, ia perlu menjadikan kerja sama energi sebagai simbol soft power regional dan bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan bentuk solidaritas yang meneguhkan identitas bersama.
Kasus Indonesia misal, jika terbentur regulasi Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), mayoritas bank swasta di Indonesia adalah bank penanaman modal asing regional, seperti CIMB, UOB, DBS, dan OCBC.
Dalam konteks ini, geoekonomi sedang bangkit sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Negara-negara berlomba menegaskan peran strategisnya dalam rantai pasok energi global. Indonesia memiliki potensi besar melalui seabed mining, yakni eksplorasi mineral dasar laut yang dibutuhkan untuk baterai dan teknologi hijau.
Namun, potensi itu harus diimbangi dengan etika ekologis. Sebab, di dunia yang makin sadar lingkungan, kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak sumber daya yang dimiliki, tetapi bagaimana sebuah negara mengelolanya dengan tanggung jawab.
Inilah bentuk soft power yang paling halus, pengaruh yang lahir dari integritas moral dan konsistensi kebijakan.Kemandirian energi sejatinya tidak akan lahir dari isolasi. Kebijakan ini tumbuh dari kemampuan sebuah negara menjadi contoh, bukan pengecualian.
Ketika Indonesia berbicara tentang bioenergi, misalnya, dunia memperhatikan apakah kebijakan itu benar-benar inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Bioetanol, sebagai bahan bakar nabati, telah menjadi yang simbol potensi sekaligus paradoks.
Murah, lokal, dan ramah lingkungan, tetapi seringkali ditentang karena kekhawatiran konversi lahan pangan, kerusakan mesin pengguna, dan ketidaksiapan masyarakat. Pada konteks ini, sosialisasi publik bukan hanya tugas teknokratis, melainkan diplomasi internal melalui cara pemerintah membangun kepercayaan rakyat terhadap masa depan yang lebih hijau. Komunikasi adalah kunci.
Sementara itu, ambisi membangun industri baterai nasional sebagai tulang punggung transisi energi juga menghadirkan dilema. Pembuatan baterai memang menjanjikan kemandirian teknologi, tetapi jika limbah dan polusinya tak terkelola, maka janji energi bersih akan menjadi kontradiksi.
Dunia tidak hanya menilai kemampuan industri kita, tetapi juga konsistensi moral kita dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Di sinilah letak diplomasi halus itu bekerja, yaitu soft power tidak tumbuh dari pencitraan, melainkan dari koherensi antara kata dan tindakan dari niat politik yang jelas.
Pertanyaan besar lainnya juga mengapa EBT masih mahal? Sebagian karena teknologi impor yang belum dikuasai penuh, sebagian karena belum tercapainya skala ekonomi yang memadai. Namun di balik biaya itu tersembunyi potensi naratif yang jarang disentuh: bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam EBT adalah investasi pada martabat bangsa.
Ketika Indonesia mampu membangun energi bersih dengan tangan sendiri, ia tidak hanya menghemat anggaran impor, tetapi juga menanamkan kepercayaan baru di mata dunia bahwa kemandirian tidak harus bertentangan dengan keberlanjutan.
Masalah pendanaan menjadi simpul utama dari semua tantangan ini. Ketergantungan pada APBN dan bantuan asing membuat banyak proyek EBT rawan terhadap diplomasi ofensif seperti dari pinjaman yang menjerat hingga pengaruh politik yang menekan.
Dalam tatanan ini, ASEAN perlu menemukan format baru, seperti intrafund mechanism, semacam dana regional yang dikelola kolektif untuk mendukung riset dan inovasi energi. Jika berhasil, inisiatif ini bisa menjadi model soft power ekonomi ASEAN pada dunia, solidaritas yang nyata, bukan seremonial.
Indonesia seharusnya tidak sekadar menjadi peserta, tetapi pemimpin. Kepemimpinan Indonesia dalam energi terbarukan akan memperkuat citra moral ASEAN sebagai kawasan yang mampu memimpin tanpa mendominasi, mengarahkan tanpa memaksa.
Bahwa energi bersih bukan sekadar alat untuk bertahan, melainkan medium untuk memperkuat identitas kawasan. Soft power Indonesia dalam konteks ini dapat muncul dalam tiga bentuk: keteladanan kebijakan, diplomasi inovasi, dan narasi moral.
Keteladanan kebijakan terlihat ketika Indonesia konsisten dengan komitmen EBT-nya, meskipun biaya awal tinggi. Diplomasi inovasi muncul saat Indonesia menginisiasi riset bersama ASEAN atau berbagi teknologi sederhana untuk negara anggota lain, yang sebenarnya sudah dijalankan. Pusat Energi ASEAN di Jakarta adalah bukti nyata.
Namun semua itu hanya akan berarti jika transisi energi diterjemahkan ke level lokal. Kemandirian energi tidak akan pernah benar-benar lahir dari ruang konferensi, melainkan dari desa-desa yang menyalakan listriknya sendiri melalui panel surya, dari petani yang memproduksi bioetanol, dari komunitas yang berani berinovasi tanpa menunggu izin pusat. Pada skala mikro itulah soft power sesungguhnya tumbuh: kekuatan yang menular, yang lahir dari keberdayaan masyarakat.
ASEAN, dengan segala keterbatasannya, masih mencari bentuk di era energi baru. Namun Indonesia memiliki posisi unik untuk menuntun arah itu dan bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan pengaruh moral yang kapasitasnya sudah teruji di kawasan Asia Tenggara.
Paris Agreement mungkin menjadi titik awal, tetapi tujuan akhirnya adalah membangun peradaban energi di mana keberlanjutan, solidaritas, dan kemandirian berjalan seiring. Jika Indonesia mampu menjadikan energi sebagai narasi atau bahasa kebudayaan, bukan sekadar komoditas, maka di situlah soft power-nya mengkristal, utuh.
(miq/miq)

 3 hours ago
1
3 hours ago
1